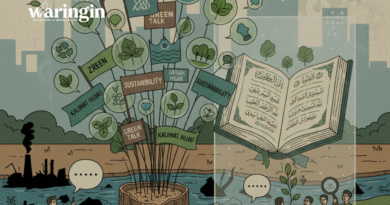Deforestasi, Seni, dan Relasi Manusia–Alam
Saya menemukan berita tentang sebuah patung kayu raksasa yang berdiri di kawasan pegunungan Dolomites melalui media sosial. Di tengah hiruk pikuk linimasa yang dipenuhi kabar politik, konflik, dan bencana alam, karya seni itu hadir sebagai jeda visual yang menenangkan. Patung kayu setinggi tujuh meter tersebut digambarkan sebagai simbol relasi manusia dan alam, sebuah upaya artistik untuk mengingatkan bahwa manusia bukanlah penguasa tunggal bumi, melainkan bagian dari ekosistem yang rapuh.
Sekilas, kekaguman muncul secara spontan. Kayu sebagai medium terasa sangat “alamiah”: ia tumbuh dari hutan, dibentuk oleh tangan manusia, lalu dikembalikan ke lanskap alam terbuka. Ada kesan bahwa seni mencoba berdamai dengan alam, bukan menaklukkannya. Namun, kekaguman itu perlahan berubah menjadi refleksi yang lebih gelisah ketika saya mengaitkannya dengan kondisi ekologis global dan terutama dengan tragedi lingkungan yang terjadi di Indonesia tahun ini, khususnya di Sumatra.
Secara global, deforestasi masih berlangsung pada skala yang mengkhawatirkan. Laporan Global Forest Watch menunjukkan bahwa dunia kehilangan sekitar 3,7 juta hektare hutan hujan primer tropis pada 2023, setara dengan hilangnya sekitar sepuluh lapangan sepak bola setiap menit. Kehilangan hutan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologis.
Indonesia termasuk dalam negara dengan tekanan tinggi terhadap hutan tropis. Meskipun ada penurunan laju deforestasi dibanding satu dekade lalu, hutan di Sumatra tetap berada dalam kondisi rentan akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Data dari World Resources Institute mencatat bahwa degradasi hutan di Sumatra berkontribusi signifikan terhadap kerusakan daerah aliran sungai, yang pada akhirnya memperparah banjir dan longsor.
Tahun ini, sejumlah wilayah di Sumatra mengalami banjir bandangdan longsor besar. Fenomena kayu-kayu berukuran besar yang hanyut bersama arus banjir menjadi simbol tragis dari relasi manusia–alam yang timpang. Pohon-pohon yang seharusnya menahan tanah dan menyerap air justru menjadi bagian dari bencana. Studi hidrologi menunjukkan bahwa deforestasi di wilayah hulu dapat meningkatkan limpasan permukaan hingga dua kali lipat, sehingga memperbesar daya rusak banjir.
Dalam konteks ini, patung kayu di Dolomites terasa seperti cermin yang memantulkan dua wajah relasi manusia dan alam. Di satu sisi, seni menghadirkan kayu sebagai simbol refleksi dan kesadaran ekologis. Di sisi lain, realitas di Sumatra menunjukkan kayu sebagai bukti kerusakan ekologis yang nyata dan mematikan. Relasi manusia–alam tidak selalu hadir dalam bentuk harmoni; sering kali ia hadir sebagai konflik antara kebutuhan ekonomi, kebijakan pembangunan, dan daya dukung lingkungan.
Pendekatan ekokritik membantu membaca ketegangan ini. Ekokritik menekankan bahwa alam bukan sekadar latar pasif bagi aktivitas manusia, melainkan entitas yang memiliki batas ekologis dan “respon” terhadap eksploitasi. Ketika hutan ditebang secara masif, alam merespons melalui krisis: banjir, longsor, kekeringan, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal.
Di sinilah seni lingkungan perlu dibaca secara kritis. Seni yang mengangkat tema relasi manusia dan alam memiliki potensi besar sebagai medium kesadaran, tetapi juga berisiko menjadi simbol kosong jika terlepas dari konteks material dan politik ekologis. Patung kayu di Dolomites memang mengundang kekaguman dan kontemplasi, tetapi pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana seni semacam ini mampu mendorong perubahan cara manusia memperlakukan alam?
Refleksi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pengalaman masyarakat di Sumatra. Laporan UN Environment Programme menegaskan bahwa masyarakat lokal dan adat adalah kelompok yang paling terdampak oleh deforestasi, meskipun mereka paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Deforestasi, dengan demikian, bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan etika relasi manusia–alam.
Seni, dalam hal ini, seharusnya tidak berhenti pada representasi estetis. Ia perlu menjadi medium kritik yang menghubungkan imajinasi ekologis dengan realitas empiris. Kekaguman saya terhadap patung kayu di Dolomites akhirnya berubah menjadi refleksi yang lebih dalam: seni dapat membuka kesadaran, tetapi tanpa perubahan struktural dalam cara manusia mengelola hutan dan alam, relasi yang timpang akan terus berulang.