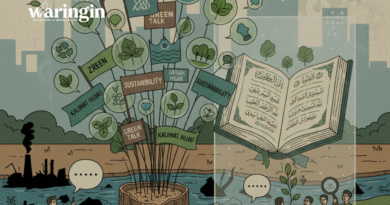Banjir Jember: Alarm Krisis Lingkungan dan Tata Ruang
Banjir kembali melanda Kabupaten Jember. Hujan deras yang turun hampir tanpa jeda dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai utama, terutama Sungai Bedadung, meluap dan merendam permukiman warga. Ribuan rumah tergenang, aktivitas lumpuh, dan sebagian warga terpaksa mengungsi. Peristiwa ini bukan sekadar bencana musiman, melainkan sinyal kuat adanya persoalan struktural dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang wilayah.
Secara meteorologis, banjir dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. Debit air sungai meningkat drastis dalam waktu singkat, sementara kapasitas alur sungai tidak mampu menampung limpasan air. Kondisi ini diperparah oleh cuaca ekstrem yang belakangan semakin sering terjadi sebagai bagian dari dinamika perubahan iklim. Namun, menyederhanakan banjir Jember sebagai semata-mata akibat hujan deras justru menutup akar masalah yang lebih dalam.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jember mengalami perubahan tata guna lahan yang signifikan, terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai. Lahan yang semula berfungsi sebagai kawasan resapan air beralih menjadi permukiman, kawasan komersial, dan infrastruktur lain. Alih fungsi ini mengurangi daya serap tanah, sehingga air hujan langsung menjadi limpasan permukaan dan mengalir ke sungai dalam volume besar. Akibatnya, sungai kehilangan fungsi alaminya sebagai pengendali banjir.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai aturan. Permukiman yang berdiri terlalu dekat dengan bantaran sungai menjadi kelompok paling rentan saat air meluap. Dalam banyak kasus, pembangunan perumahan di wilayah rawan banjir tidak disertai kajian risiko lingkungan yang memadai. Ketika bencana datang, warga menjadi pihak yang menanggung dampak paling besar, sementara aspek perencanaan jarang disorot secara serius.
Dari sisi teknis, pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tumpukan sampah mempersempit alur air. Minimnya normalisasi sungai dan lemahnya pengelolaan drainase perkotaan membuat air meluap ke jalan dan permukiman. Drainase yang tersumbat menjadikan genangan bertahan lebih lama, memperparah kerusakan dan memperbesar risiko penyakit pascabanjir.
Dampak banjir dirasakan langsung oleh masyarakat. Ribuan rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi, dari selutut hingga mencapai dada orang dewasa di beberapa titik. Perabot rumah tangga rusak, dokumen penting hilang, dan aktivitas ekonomi terhenti. Bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan pekerja sektor informal, banjir berarti kehilangan rasa aman sekaligus sumber penghidupan.
Infrastruktur publik juga terdampak. Sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui, akses antarwilayah terganggu, bahkan jembatan di beberapa lokasi mengalami kerusakan. Kondisi ini menyulitkan distribusi bantuan dan memperlambat proses pemulihan. Selain itu, banjir mencemari sumber air bersih warga. Sumur-sumur terendam lumpur dan limbah, meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi kulit.
Lebih jauh, banjir di Jember menyingkap persoalan ketimpangan ekologis. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan sering kali adalah kelompok dengan pilihan terbatas, sementara keputusan pembangunan dan tata ruang ditentukan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam konteks ini, banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana sosial akibat kegagalan tata kelola lingkungan.
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Penanganan darurat seperti distribusi bantuan dan evakuasi memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi langkah preventif jangka panjang. Normalisasi sungai, penegakan aturan sempadan sungai, rehabilitasi kawasan hulu, serta perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana harus menjadi agenda utama.
Banjir Jember adalah alarm keras bahwa relasi manusia dengan lingkungannya tengah bermasalah. Tanpa perubahan paradigma dari eksploitasi menuju keberlanjutan, bencana serupa akan terus berulang, dengan korban yang semakin besar. Di titik ini, banjir tidak lagi bisa dipahami sebagai kejadian luar biasa, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam.