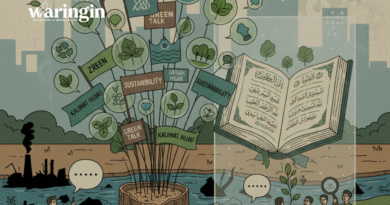Mendorong Partisipasi Santri dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan
Dalam banyak perdebatan tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, suara masyarakat lokal kerap berada di posisi paling pinggir. Kebijakan lahir dari meja-meja kekuasaan, dirumuskan dengan bahasa teknokratis, dan dibungkus jargon pembangunan, sementara mereka yang hidup paling dekat dengan alam justru jarang diajak bicara. Negara dan pasar seolah bersepakat menentukan nasib tanah, laut, dan hutan, dengan asumsi bahwa eksploitasi adalah jalan satu-satunya menuju kemajuan. Di tengah situasi semacam ini, kehadiran santri dalam isu-isu ekologis menjadi menarik sekaligus penting untuk dibaca secara lebih serius.
Santri sering dipersepsikan sebagai kelompok religius yang berkutat pada urusan ibadah, kitab kuning, dan ritual keagamaan. Namun pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa santri tidak selalu berada di ruang privat agama. Dalam konteks tertentu, mereka justru tampil sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan publik, terutama ketika kebijakan tersebut menyentuh langsung ruang hidup warga. Di sinilah santri mulai beralih dari sekadar subjek keagamaan menjadi aktor sosial-politik yang sadar akan ketimpangan struktural.
Kasus penolakan tambang pasir besi di wilayah pesisir Paseban, Jember, menjadi contoh bagaimana santri membaca persoalan lingkungan bukan sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai masalah keadilan. Penolakan tersebut tidak lahir dari romantisme alam atau sentimen emosional belaka, tetapi dari kesadaran bahwa tambang akan mengubah relasi masyarakat dengan ruang hidupnya. Laut, pasir, dan pesisir bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan keberlanjutan hidup warga.
Yang menarik, keterlibatan santri dalam kasus ini tidak berhenti pada aksi protes. Mereka terlibat dalam pendidikan warga, diskusi-diskusi publik, advokasi kebijakan, hingga pendampingan hukum bagi masyarakat yang mengalami kriminalisasi. Artinya, santri tidak hanya bergerak di jalan, tetapi juga masuk ke wilayah yang lebih kompleks: membangun kesadaran, memperkuat posisi tawar warga, dan membuka ruang partisipasi alternatif ketika jalur formal negara tertutup.
Partisipasi santri dalam isu SDA tentu tidak muncul begitu saja. Ia berakar pada cara pandang keagamaan yang menempatkan alam sebagai amanah, bukan komoditas. Dalam tradisi Islam, manusia tidak diposisikan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai penjaga yang bertanggung jawab. Perspektif ini memberi landasan etis yang kuat bagi santri untuk menolak kebijakan yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat. Dalam konteks Paseban, penolakan tambang dimaknai sebagai upaya menjaga kehidupan bersama, bukan sekadar konflik kepentingan ekonomi.
Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua santri memiliki sikap yang sama. Identitas santri tidak otomatis progresif atau kritis. Di beberapa tempat, sebagian elit keagamaan justru memilih bersikap pragmatis atau diam karena kedekatan dengan kekuasaan lokal dan kepentingan ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa posisi santri sangat ditentukan oleh konteks sosial, afiliasi organisasi, dan keberpihakan politik. Karena itu, membicarakan santri sebagai agen perubahan ekologis harus disertai dengan kesadaran bahwa mereka juga berada dalam relasi kuasa yang tidak sederhana.
Di titik ini, partisipasi santri perlu dipahami sebagai proses yang memerlukan penyadaran kritis dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Tanpa itu, keterlibatan santri berisiko berhenti pada mobilisasi sesaat yang reaktif terhadap kasus tertentu. Gerakan yang berbasis kemarahan atau ancaman langsung sering kali kuat di awal, tetapi melemah ketika konflik mereda atau ketika tekanan politik meningkat.
Catatan kritis lain yang perlu diajukan adalah kecenderungan gerakan santri yang masih berbasis kasus. Penolakan tambang, reklamasi, atau proyek ekstraktif lain sering kali muncul sebagai respons terhadap ancaman konkret, tetapi belum diikuti dengan upaya sistematis untuk masuk ke tahap perumusan kebijakan. Pengawalan tata ruang, regulasi perizinan, atau peraturan desa masih jarang menjadi fokus utama. Padahal, di situlah keputusan-keputusan strategis tentang pengelolaan SDA sebenarnya ditentukan.
Selain itu, narasi keagamaan yang digunakan dalam gerakan ekologis santri juga perlu terus direfleksikan. Pendekatan moral seperti “maslahat versus mafsadat” memang penting, tetapi jika digunakan secara simplistis, ia bisa menutup kompleksitas persoalan. Kebijakan tambang, misalnya, tidak hanya soal baik dan buruk secara moral, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi-politik yang lebih luas: relasi negara dan korporasi, logika pembangunan ekstraktif, serta ketimpangan distribusi manfaat dan risiko.
Tantangan ke depan adalah bagaimana santri mampu mengintegrasikan etika Islam dengan analisis struktural. Artinya, kritik terhadap kebijakan SDA tidak berhenti pada seruan moral, tetapi juga menyasar sistem yang memungkinkan eksploitasi berlangsung terus-menerus. Di sinilah santri dituntut untuk memperkuat kapasitas intelektualnya, membangun jejaring dengan organisasi masyarakat sipil, dan berani berhadapan dengan negara serta pasar secara kritis namun strategis.
Pengalaman Paseban menunjukkan bahwa santri memiliki potensi besar sebagai agen perubahan ekologis. Potensi ini menjadi signifikan ketika santri tidak hanya berbicara atas nama agama, tetapi juga berpihak pada masyarakat yang terdampak langsung. Namun potensi tersebut hanya akan bermakna jika diiringi dengan konsistensi, refleksi kritis, dan strategi jangka panjang. Tanpa itu, gerakan santri berisiko melemah, terkooptasi, atau terjebak dalam romantisme perlawanan.