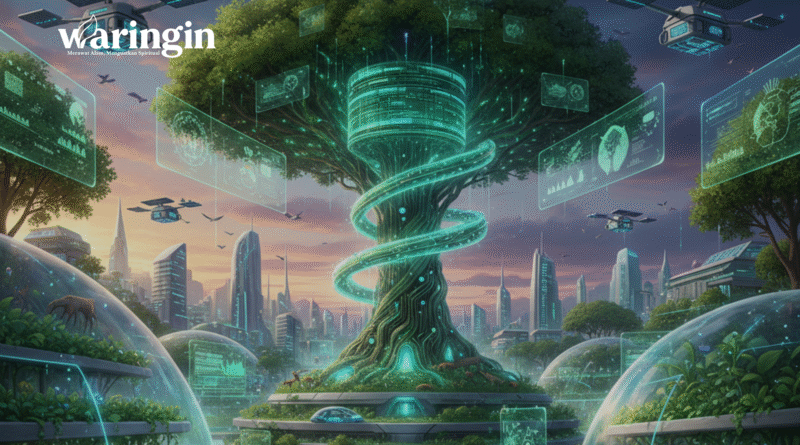Teknologi, AI, dan Dosa Ekologis yang Jarang Kita Akui
Di zaman ketika krisis iklim semakin nyata, teknologi sering datang dengan wajah optimisme. Kita diyakinkan bahwa kecerdasan buatan, data besar, dan algoritma canggih akan membantu manusia mengatasi kekacauan ekologis yang kita ciptakan sendiri. Dari prediksi banjir hingga pengelolaan kota pintar, teknologi diposisikan sebagai jawaban rasional atas krisis yang terasa makin tak terkendali. Ada harapan atau mungkin ilusi bahwa dengan cukup kecerdasan buatan, bumi bisa diselamatkan tanpa kita harus banyak mengubah cara hidup.
Namun, di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: benarkah teknologi bekerja di ruang yang netral?
Teknologi, termasuk AI, tidak pernah hadir sendirian. Ia lahir dari cara manusia memandang dunia, dari sistem ekonomi yang memberi arah, dan dari logika kekuasaan yang menentukan untuk siapa ia bekerja. Ketika teknologi dikembangkan dalam kerangka pertumbuhan tanpa batas, efisiensi ekstrem, dan akumulasi keuntungan, maka ia cenderung memperlakukan alam sebagai sesuatu yang bisa diatur, dimodifikasi, bahkan dikorbankan. Alam menjadi persoalan teknis, bukan relasi etis.
Paradoks ini terlihat jelas pada infrastruktur AI itu sendiri. Di balik kecanggihan model-model kecerdasan buatan, ada pusat data raksasa yang mengonsumsi listrik dan air dalam jumlah luar biasa. Banyak di antaranya masih bergantung pada energi fosil dan dibangun di wilayah yang secara ekologis rapuh. Air yang digunakan untuk mendinginkan server sering diambil dari daerah yang warganya justru menghadapi krisis air bersih. Teknologi yang dijanjikan sebagai alat penyelamat iklim diam-diam ikut mempercepat kerusakan ekologis.
Di sinilah ekoteologi memberi bahasa untuk menyebut apa yang sering luput dari perhatian: dosa ekologis yang bersifat struktural. Bukan dosa personal dalam arti moral sehari-hari, melainkan dosa yang tertanam dalam sistem produksi pengetahuan dan teknologi. Dosa yang muncul ketika manusia merasa mampu mengendalikan segalanya, lalu menempatkan teknologi sebagai solusi utama, sambil menyingkirkan pertanyaan tentang keadilan, relasi, dan tanggung jawab.
Cara berpikir ini bukan hal baru. Ia merupakan kelanjutan dari antroposentrisme modern keyakinan bahwa manusia adalah pusat, penguasa, sekaligus pengelola sah bumi. Jika dulu dominasi ini dilegitimasi lewat tafsir keagamaan yang keliru tentang “berkuasa atas alam”, kini ia diteruskan lewat bahasa algoritma dan data. AI memberi kesan bahwa dunia bisa dipetakan, diprediksi, dan dikontrol sepenuhnya. Bahwa krisis iklim hanyalah persoalan kurang data atau kurang komputasi.
Masalahnya, krisis ekologis bukan semata krisis teknis. Ia adalah krisis relasi. Relasi manusia dengan alam, relasi antara yang kaya dan yang miskin, serta relasi antara pusat-pusat kekuasaan global dan wilayah pinggiran yang menanggung dampak terburuk. Ketika AI dikembangkan terutama oleh dan untuk kepentingan ekonomi kuat, sementara beban ekologisnya ditanggung masyarakat rentan di Selatan Global, teknologi menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri.
Ekoteologi tidak menolak teknologi. Ia justru menolak penyembahan terhadap teknologi. Dalam tradisi teologi ciptaan, manusia dipahami sebagai penjaga, bukan pemilik mutlak bumi. Dari sini, teknologi seharusnya menjadi alat untuk merawat kehidupan, bukan mempercepat eksploitasi. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: teknologi ini melayani siapa, dan dengan biaya siapa?
Bayangkan jika kecerdasan buatan tidak diarahkan untuk memperbesar konsumsi, melainkan untuk memperkuat daya tahan komunitas. Jika ia membantu petani kecil membaca perubahan cuaca, membantu warga kota miskin menghadapi banjir, atau membantu komunitas adat menjaga wilayah hidup mereka. Dalam logika seperti ini, teknologi tidak lagi berdiri di atas alam, melainkan berjalan bersama kehidupan.
Krisis iklim menuntut lebih dari sekadar inovasi. Ia menuntut perubahan cara pandang. Selama kita masih percaya bahwa kecerdasan buatan dapat menggantikan pertobatan ekologis, perubahan gaya hidup, pembongkaran sistem ekonomi yang timpang, dan keberanian politik, maka teknologi hanya akan menjadi penundaan yang mahal. Kita menunda perubahan dengan membayar harga yang lebih besar, dan sering kali harga itu dibayar oleh mereka yang paling tidak bertanggung jawab atas krisis ini.
Pada akhirnya, AI bukan cermin kecerdasan manusia, melainkan cermin cara kita memaknai kekuasaan. Jika ia dikembangkan tanpa etika relasional dan kesadaran spiritual, ia hanya akan memperhalus wajah lama dari dominasi manusia atas bumi. Tetapi jika teknologi ditempatkan kembali sebagai alat, bukan tuhan, maka masih ada ruang untuk menjadikannya bagian dari pertobatan ekologis yang lebih jujur. Masa depan bumi tidak ditentukan oleh seberapa canggih algoritma kita, melainkan oleh seberapa rendah hati manusia dalam hidup bersama ciptaannya.